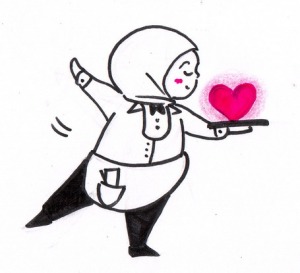Setelah sekian lama akhirnya menulis lagi. Ini adalah lanjutan dari “Kembang Wangi”. Banyak yang tidak memahami cerita itu. Ya gak masalah juga kalau tidak paham. Biarkan sahaja semuanya mengalir, dan nikmatilah!
Ini adalah cerita yang kutulis juga untuk menyalurkan sedikit hitam dalam hati saya setelah mengalami banyak kekecewaan. Daripada saya getir, lebih baik mencari penyelesaian lewat fiksi. Ya nggak?
Seperti biasa, jangan pikirkan hal-hal teknis saat membaca dan biarkan semuanya mengalir. Selamat membaca!
-nyaw, kembali menulis fiksi-
***
Jejak Jemari Harum Melati

Kembang Wangi adalah pelacur yang tinggal seorang diri. Tanpa mama germo maupun seorang pun kawan. Sebenarnya, sebelumnya, keadaannya tidak demikian. Pada awalnya Kembang Wangi tidak seorang diri. Dan rumahnya yang serupa liang, tidak hanya berisi dirinya seorang. Dan pada awalnya, rumahnya tidak pernah sepenuhnya sepi. Dan sebelum ini, tidak hanya pikir dan khayalan yang menjadi teman kesendirian Kembang Wangi. Dan dulu tidak hanya tanya, “Mengapa saya adalah pelacur perawan?” yang menjadi pengisi kekosongan dalam diri Kembang Wangi.
Ya betul. Dulu keadaannya tidak seperti ini. Dulu, Kembang Wangi bukan satu-satunya pelacur yang mengisi rumahnya yang serupa liang. Dulu ada Kembang Wangi dan seorang lagi yang bernama Harum Melati. Kembang Wangi perawan tapi Harum Melati bukan. Karena Harum Melati adalah ibu kandung dari Kembang Wangi. Dan kehormatan melahirkan selagi perawan hanya milik Maryam. Jadi sudah barang tentu Harum Melati sudah tidak perawan.
Tapi selain sudah tidak perawan dan melahirkan yang menjadi pembeda Harum Melati dan Kembang Wangi, masih ada hal-hal lain. Hal lain seperti tingkat kebijaksanaan dan cara mencerna kehidupan. Harum Melati kalah bila dibandingkan dengan Kembang Wangi dalam dua hal ini. Memang itu adalah fakta yang aneh, tapi cukup nyata. Mungkin karena menjadi seorang ibu tidak selalu menandakan bertambahnya kebijaksanaan. Kalau cukup sial, menjadi seorang ibu hanya berakhir sebagai seseorang yang telah melahirkan. Sudah cukup sampai di sana.
Sayangnya, Harum Melati terhenti sebagai sebagai seorang ibu yang melahirkan. Dan memang sangat disayangkan ia tidak mendapatkan apa-apa dari kehidupannya yang selanjutnya. Kebijaksanaannya tidak bertambah, dan ia tidak pernah sepenuhnya dapat mencerna hal-hal yang telah menimpanya. Kalau ia berhasil mencerna segalanya dan mendapatkan kebijaksanaan darinya, sudah barang tentu ia tidak akan melakukan hal yang telah dilakukannya. Dan kalau ia tidak melakukan hal yang telah dilakukannya, maka Kembang Wangi tidak akan tinggal seorang diri. Dan mungkin Kembang Wangi tidak akan menjadi pelacur yang selalu perawan. Dan mungkin saja Kembang Wangi akan mengerti keperawanan para pelacur di dalam garis keluarganya.
Tapi tidak. Harum Melati telah melakukan hal yang telah dilakukannya. Suatu hal yang telah dilakukan oleh ibunya. Juga neneknya. Dan tak luput nenek dari neneknya. Tentu saja tak ketinggalan nenek dari nenek neneknya. Hal yang telah dilakukan oleh para perempuan pendahulu Kembang Wangi telah meninggalkan sebuah luka di dalam hatinya. Ketika mengingat hal yang telah dilakukan ibunya, Kembang Wangi hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya pelan sambil berdecak. Ia akan melepas napas panjang dan berkata,
“Ah Ibu. Mengapa kau mengulang sejarah? Mengapa kau melakukan hal yang telah dilakukan nenek? Padahal kau tahu laki-laki itu seperti kupu-kupu. Lalu kami perempuan….”
Biasanya Kembang Wangi tidak akan melanjutkan kata-katanya. Karena ujung dari kata-kata itu selalu berhasil membuatnya resah. Kedua matanya pun akan menjadi basah karena gelisah memikirkan nasib para neneknya. Terutama kalau memikirkan nasib ibunya sendiri. Harum Melati.
Dulu ketika Kembang Wangi hanya setinggi lutut orang dewasa dan tangannya belum mencapai telinganya yang di seberang, Harum Melati sering menuturkan sebuah kisah. Kisah yang menemani Kembang Wangi ketika ia masih sering dimandikan. Kisah yang menjadi pelantun ketika badannya dibedaki dan dipakaikan baju ringan berwarna-warni lembut. Dan kisah ini kemudian diteruskan, sambil rambut Kembang Wangi yang masih sebahu disisir sembari Harum Melati mencari telur kutu putih.Pada saat seperti ini, kisah Harum Melati memuncak dan menjadi menarik.
Kisah yang dituturkan oleh Harum Melati adalah mengenai asal-usul dirinya dan Kembang Wangi. Di dalamnya ada kisah mengenai takdir mereka. Dan paling penting, sesekali akan terselip kisah mengenai ayah kandung Kembang Melati. Meskipun hanya kisah yang berukuran sedikit, tapi terasa seperti harta bagi Kembang Melati yang tidak pernah bertemu ayahnya.
Pada suatu hari Harum Melati memulai kisahnya. Ia memulainya dengan sebuah gerakan sisiran membelah dan menjentik telur kutu putih di atas kepala Kembang Wang. Harum Melati memulai kisahnya dengan suara yang halus namun bernada riang. Kata-kata itu meluncur dengan tenang,
“Tahukah Kembang Wangi, tahukah kamu bahwa kita adalah keluarga pelacur perawan?”
Kembang Wangi yang masih kecil dan masih setinggi lutut, hanya diam dan memejamkan mata. Ia terlarut dalam buaian suara halus ibunya dan telisik jari jemari gemulai di antara rambutnya yang lurus halus. Sambil memejam, Kembang Wangi hanya memusatkan perhatian pada rasa nyaman. Karena duduk membelakangi ibunya, ia hanya dapat membayangkan seperti apa mimik muka ibunya saat ini.
Kembang Wangi membayangkan bahwa Harum Melati sedang tersenyum kecil. Bibir yang tersungging pada oval muka wajah ibunya akan menularkan warna pastel ayu yang menjalar dari pipi kiri ke kanan. Ke lesung kiri lalu ke lesung kanan. Pink dan pink. Pink dan pink di atas kulit yang sedikit sawo matang. Pada sawo matang itu tersembunyi dua mutiara hitam yang dinaungi oleh sepasang bulu mata lebat dan alis serupa garis lurus tenang yang teduh. Kesemuanya dibingkai oleh rambut lurus legam yang yang jatuh seperti benang-benang berat dan licin. Rambut yang serupa dengan rambut Kembang Wangi.
Seperti itulah Kembang Wangi membayangkan ibunya berkisah. Seperti itulah Kembang Wangi pikir Harum Melati memulai cerita. Jadi Kembang Wangi biasanya hanya tenang. Karena ia tahu kalau ia tenang, maka Harum Melati akan terus saja berkisah. Dan memang seperti itu. Karena Kembang Wangi yang hanya setinggi lutut duduk terdiam, maka Harum Melati akan melanjut dengan tenang,
“Ya Kembang Wangi, kita keluarga pelacur perawan. Nenekmu pelacur, aku pelacur, dan bahkan kelak kamu akan menjadi pelacur. Tapi kita perawan. Sialnya kita adalah pelacur perawan!”
Kembang Wangi yang masih belum mengerti sepatah kata pun tetap duduk terdiam. Ia menikmati telisik dan jentikan gemulai jari jemari ibunya. Kembang Wangi menikmati semua itu meskipun di dalam hatinya ada tanya mengenai istilah “pelacur”, “perawan”, dan apa hubungan keduanya dengan kesialan.
Tapi Kembang Wangi memilih diam. Ia merasa kalau ia hanya diam, maka Harum Melati pasti akan melanjutkan ceritanya. Dan memang benar, kata-kata kembali meluncur halus dari mulut Harum Melati. Dan dengan tenang ia melanjut, meskipun dengan sedikit nada getir,
“Karena kita pelacur yang perawan, maka lelaki merasa segan. Lalu segan menjadi tertekan. Dan rasa tertekan akan mengeluarkan rasa yag teredam. Rasa yang berasal dari hati terdalam.”
Harum Melati terhenti sedikit tersentak seakan-akan ia baru menyadari makna di dalam kata-katanya sendiri. Juga tersentak karena tidak makna yang mendalam itu memunculkan secercah ragu pada kelanjutan ceritanya. Seakan-akan ada sesuatu yang enggan ia katakan. Sesuatu itu membuat pita suaranya sempit dan lidahnya kelu. Bibirnya serasa terbelenggu. Dan mulai terdapat gemetar di dalam gemulai jari jemarinya.
Dengan gerakan yang sedikit patah dan kaku, Harum Melati kembali menyisir di antara lurus halus rambut Kembang Wangi yang serupa dirinya. Ia terus lewatkan sisir sambil mengumpulkan keberanian untuk bertutur pada anaknya yang baru setinggi lutut itu. Helaian-helaian halus anak yang telah memecah perawan rahimnya terasa menenangkan sekaligus menyakitkan. Menenangkan karena mengingatkannya pada hari-hari ketika satu-satunya masalah yang ia punya hanyalah seputar keperawanan. Menyakitkan karena Kembang Wangi mengingatkannya pada lelaki yang tidak segan untuk meniduri pelacur yang perawan.
Lelaki tanpa segan itulah ayah kandung dari Kembang Wangi. Lelaki itu selalu membuat lidah Harum Melati terkunci sekaligus tergelitik untuk berkisah. Karena pada satu titik kecil, pertemuan itu terasa indah. Meskipun hanya sebelah.
Tetapi keindahan yang hanya sebelah, jarang-jarang menenangkan. Banyaknya yang membuat gelisah. Maka Harum Melati kesulitan tenang ketika kenangan lelaki itu membayang. Air mata mulai menggenang pada sudut-sudut matanya. Dan tangan Harum Melati semakin gemetar hingga sisir yang melewati lurus halus rambut Kembang Wangi hendak lepas.
Dengan tekad kuat yang tiba-tiba muncul, Harum Melati menguatkan genggaman pada sisir itu. Seakan-akan sisi itu adalah jiwanya yang hendak lepas. Dan diteruskannya menyisir meskipun dengan sedikit gemetaran.
Perasaan yang tertahan di dalam diri Harum Melati menjadi energi yang dapat melepaskan kelu pada bibirnya. Ia pun meneruskan kisah itu. Kisah mengenai ayah kandung Kembang Wangi. Kisah mengenai lelaki yang tidak segan-segan memerawani.
“Kau harus tahu Kembang Wangi. Kau harus tahu tentang ayahmu. Dia lelaki yang tidak seperti para lelaki yang lainnya lagi. Coklat matanya sama dalamnya dengan dalamnya coklat matamu. Ah tidak hanya matany saja yang dalam, semua yang ada pada dirinya terasa dalam. Karena ia punya kesedihan yang dapat membuat tenggelam. Tenggelam jauh, jauh ke dalam. Larut dalam kalutnya yang mendalam.”
Di sini Harum Melati lagi-lagi terdiam. Hampir-hampir Kembang Wangi yang hanya setinggi lutu tidak bersabar. Ia hampir membalikkan badan. Tapi tiba-tiba Harum Melati melanjut,
“Ia lelaki yang kalut. Ia lelaki yang kalah. Ia lelaki yang membiarkan dirinya menjadi kacung kehidupan. Ia tidak pernah benar-benar ada. Ia hanya sekadar ada. Ia hanya bertahan dari menit ke menit berikutnya sambil mencoba untuk tidak menjerit.
“Ia begitu sibuk hidup hingga tidak sadar bahwa ia sedang dikerjai habis-habisan. Harusnya ia mencari inti kebenaran dalam dirinya, tapi ia malahan menemukan orang lain. Ia menemukan seorang perempuan. Dan perempuan itu menjadi segalanya. Patokan, tumpuan, alasan untuk menjadi ada. Segalanya. Hanya segalanya.
“Tapi seorang lelaki, sekalipun sangat menawan, jarang-jarang diperbolehkan memiliki segalanya. Oleh karenanya, perempuan yang merupakan segalanya itu segera pergi meninggalkan ayahmu seorang diri. Ayahmu menjadi sebuah cangkang. Sebuah cangkang dari kesedihan yang pekat.”
Setelah tutur yang begitu panjang, kata-kata Harum Melati terasa berhenti begitu mendadak pada akhirnya. Kembang Wangi tahu bahwa kisah itu belum selesai, meskipun rambutnya yang lurus halus telah rapi karena disisir berkali-kali. Maka Kembang Wangi membiarkan Harum Melati terus menyisir. Jari jemari gemulai yang menenangkan itu terdengar begitu menenangkan. Jari jemari itu mulai menjali helai-helai rambutnya menjadi kepang dan lilitan.
Sembari mengepang, Harum Melati kembali terbuai dalam kenang mengenai lelaki yang menjadi ayah kandung dari anaknya yang semata wayang. Ia teringat pada langkah lelaki itu yang begitu cepat. Seakan-akan ia hendak minggat dari semua semua kalutnya. Kalut yang ia artikan sebagai sesosok Harum Melati. Kalut yang sebenarnya tidak pernah berhubungan dengan Harum Melati, tapi berkenaan dengan perempuan lain. Tapi karena Harum Melati adalah pelacur, maka ialah yang salah, ialah biang masalah. Ialah yang seharusnya dihindari dan ditinggalkan. Sekalipun sudah tidak perawan, malahan sampai mengandung.
Anak yang dikandung selama sembilan bulan oleh Harum Melati itu kini telah besar. Ia cantik menarik meskipun baru setinggi lutut. Dan kecantikan di dalam dalam coklat matanya begitu menular seperti wangi sebuah kembang yang dapat membuat pikiran seseorang menerawang. Kembang Wangi. Begitu pantasnya nama itu.
Kembang Wangi yang sudah tidak sabar dengan kelanjutan cerita mengeluarkan semacam pekik. Sebuah bunyi yang memaksa Harum Melati kembali berkisah. Dengan tutur-tutur halus yang mengambang. Kembang Wangi bertanya, dengan sedikit memaksa,
“Lalu bagaimana kalian bertemu Bu? Bagaimana aku sampai lahir?”
Sebuah hening menjadi awal jawaban, lalu Harum Melati menjawab, “Kurasa ayahmu berhasil mengendus harumku. Mungkin karena ia butuh melepaskan diri dari cangkangnya.”
Kembang Wangi mengernyit dan bertanya, “Apakah Ibu berhasil membantu ayah?”
“Iya Nak.”
“Lalu mengapa ayah tidak pernah kembali?”
Hening kembali menjadi jawab. Tapi ini adalah hening yang berbeda. Hening kali ini memberi firasat bagi Kembang Wangi agar terdiam dan berhenti bertanya. Hening itu telah membungkam kata-kata di dalam mulut ibunya. Terdapat suatu kerut bingung yang sangat samar pada kening Harum Melati yang tiba-tiba saja kehilangan cahaya.
Oleh karena itu Kembang Wangi biarkan Harum Melati menyelesaikan kepang dan lilitan pada kepalanya. Kepang dan lilitan itu mengelilingi kepala Kembang Wangi seperti sebuah mahkota. Ketika cahaya matahari menimpa kepala kecil Kembang Wangi, ia seakan-akan mengeluarkan cahayanya lembutnya tersendiri. Cahaya halus perawan yang belum pernah dikotori. Begitu bersih. Begitu perawan.
Harum Melati kembali mengenang lelaki yang telah mengambil perawannya dan menjadikannya sekadar pelacur. Pikirannya menerawang pada pertanyaan, “Lalu mengapa ayah tidak pernah kembali?” dengan perasaan sakit yang menganga. Harum Melati tidak pernah tahu apa jawab dari pertanyaan itu. Ia sendiri sering sekali bertanya seperti itu pada dirinya sendiri,
“Mengapa ia tidak pernah kembali? Mengapa tidak pernah sekali pun?”
Padahal Harum Melati menunggu setiap malam di luar rumahnya serupa liang. Ia bilang ia sedang menjajakan badan, padahal badannya tidak pernah bersedia. Badannya hanya miliki lelaki yang pernah mengambil perawannya. Tapi lelaki itu tidak pernah kembali. Tidak pernah sekali pun.
Mungkin lelaki itu tidak akan kembali. Karena sekarang Harum Melati bukan lagi pelacur perawan, tapi sudah menjadi pelacur. Hanya pelacur. Sekalipun badannya tidak sekali pun tersentuh selain oleh lelaki yang mengambil perawannya. Lelaki yang merupakan ayah kandung Kembang Wangi.
Atau mungkin lelaki itu hanya menyadari bahwa ia menginginkan perempuan yang tidak sekadar pelacur. Perempuan yang dapat menjadi segalanya. Seperti perempuan yang telah pergi dan meninggalkannya menjadi cangkang. Ia butuh perasaan itu lagi. Perasaan bahwa ia memiliki segalanya padahal segalanya itu pergi bersama sesosok perempuan. Samar-samar Harum Melati teringat kata-kata lelaki itu,
“Aku tidak bisa berdamai dengan pelacur yang sudah tidak perawan semacam kamu. Aku tidak bisa berdamai dengan perempuan dengan kualitas kesekian. Aku adalah lelaku yang ditakdirkan untuk mendapatkan segalanya. Dan aku tidak akan pernah bisa berdiam di dalam dekapan perawan yang sudah tidak perawan.”
Mengingat kata-kata terakhir lelaki itu sebelum meninggalkan dirinya dan Kembang Wangi di dalam kamdungannya, membuat hati Harum Melati kecut. Cahaya matanya kian redam. Lama kelamaan kecut itu berubah menjadi pahit. Begitu pahitnya karena Harum Melati kini mengerti apa yang telah benar-benar menimpanya. Ia mengerti bahwa ia telah djadikan perempuan kelas kesekian, hanya karena ia adalah pelacur. Dan jabang bayi di dalam rahimnya, tidak menjadikannya mulia seperti layaknya perempuan. Malah menjadikannya rendahan.
Melihat kekosongan di dalam mata ibunya, Kembang Wangi menghambur ke dalam pelukannya. Harum Melati hanya membalas dengan pelukan kecil dan menyuruhnya bermain di luar. Awalnya Kembang Wangi enggan, ada sebuah rasa khawatir di dalam dirinya yang membuatnya mengencangkan pelukan, Tapi Harum Melati tidak menggubris kekhawatiran itu. Dengan lembut, dilepaskannya pelukan Kembang Wangi dan kembali menyuruhnya bermain di luar.
Anak perempuan yang hanya setinggi lutut itu kemudian berdiri dan beranjak pergi. Sebelum melewati pintu rumah liang yang telah berdecit itu, ia melirik. Di ujung mata ia melihat ibunya, Harum Melati, tersenyum kecil. Kembang Wangi melambaikan tangan kecil yang dibala Harum Melati dengan sebuah senyuman yang menjalar dari lesung kiri ke lesung kanan. Pink dan pink di atas kulit sawo matang. Lengkap dengan dua mutiara hitam yang bersinar.
Melihat mimik muka cantik ibunya, Kembang Wangi berkata pada dirinya sendiri, “Ah Ibu tidak apa-apa. Buktinya ibu tersenyum. Mungkin masalah kepergian ayahnya sebenarnya hal kecil.”
Sayangnya apa yang ada di dalam pikiran Kembang Wangi meleset. Ketika ia pulang, pintu depan kecil rumahnya yang serupa liang sudah menganga. Terdapat sebuah bayang panjang tidak wajar yang memenuhi ruang. Sebuah bayang tubuh yang melayang. Sebuah bayangan yang terayun-ayun dari tubuh yang menggantung dari langit-langit. Tubuh Harum Melati.
Kembang Wangi menjerit ketika menyadari bayangan yang melayang-layang itu berasal dari tubuh Harum Melati yang menggantung dari langit-langit. Di tempat yang biasanya tergantung sebuah bohlam, kini menjadi tempat tali yang menggantungkan tubuh Harum Melati. Baru kali ini Harum Melati melihat mimik muka yang begitu mengerikan terpasang pada wajah ibunya. Mata dan mulutnya menganga dan tergambar sebuah ekspresi kesedihan mendalam pada wajah yang biasanya begitu meneduhkan.
Kembang Wangi terpaku melihat mimik muka terakhir dari ibunya. Kembang Wangi masih terpaku ketika warga sekitar berhamburan memasuki rumahnya setelah mendengar jeritannya yang melolong. Semua warga yang melihat terkejut tidak kepalang melihat tubuh Harum Melati tergantung, berayun-ayun ti tengah rumah yang serupa liang. Seorang ibu cepat-cepat memalingkan mata Kembang Wangi dari pemandangan mengerikan itu. Tapi sayangnya sudah terlambut. Kenangan tubuh Harum Melati yang gantung diri telah terpatri dalam ingatan Kembang Wangi.
Harum Melati yang memilih gantung diri tak hanya meninggalkan sebuah ingatan yang mengerikan dan sebentuk rumah yang serupa liang. Ia meninggalkan kepang dan lilitan pada kepala Kembang Wangi yang tidak bersedia ia uraikan hingga beberapa tahun kemudian. Ia juga meninggalkan sebuah surat. Surat itu baru bisa dibaca Kembang Wangi yang masih berkepang hingga tiga tahun kemudian. Tubuhnya tidak lagi setinggi lutut dan ia sudah lancar baca tulis. Kepang dan lilitan yang memebentuk mahkota pada kepalanya memudar menjadi coklat. Coklat yang dalam seperti matanya dan mata ayah kandungnya.
Surat itu berisi tulisan yang tidak rapi dan beberapa sisa bercak yang terlihat seperti bekas air yang mengering. Mungkin bercak yang berasal dari tetesan air mata Harum Melati yang menulis pesan terakhir sambil menangis. Isi surat itu tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Tapi maknanya mengambang. Kurang lebih seperti kisah-kisah Harum Melati. Di dalam surat itu Harum Melati menulis,
“Kembang Wangi, ibumu kini telah menjadi cangkang seperti ayahmu. Tapi kini ibumu cangkang yang kosong. Karena ayahmu telah membawa segala yang ada padaku. Bahkan kesedihan dan terutama harga diri. Ayahmu telah membawa setiap segala yang ada dalam ibumu ini.
Betapa tidak adilnya. Terlahir sebagai pelacur tapi hanya bisa menjadi perawan. Begitu tidak perawan, ditinggalkan dan dihempaskan. Padahal semua perempuan seperti kita. Semua perempuan seperti ini. Lalu mengapa hanya kita yang akan menjadi terbuang?
Betapa tidak adilnya. Laki-laki adalah kupu-kupu, sedangkan perempuan hanya bisa menjadi kembang. Duduk menunggu lalu ditinggal terbang.”
Kembang Wangi yang sudah tidak lagi selutut hanya bisa terdiam. Ia terdiam cukup lama setelah membaca surat itu. Tiba-tiba ia meraih puncak kepalanya dan mulai mengurai kepang yang tak ia lepas sejak tiga tahun yang lalu. Kepang dan lilitan yang telah dijalin begitu hati-hati oleh Harum Melati, diuraikannya. Ikal-ikal dengan semburat coklat yang dalam, berjatuhan dengan lembut pada pundaknya. Ikal-ikal itu terbentuk dari jejak jalinan yang dibuat oleh jari jemari gemulai Harum Melati. Kini jalinan itu terburai dan meninggalkan sebuah kenangan sebentuk ikal.
Ikal itu kemudian tidak hilang hingga bertahun-tahun kemudian. Terus meninggalkan lekuk jejak pada rambut Kembang Wangi yang berubah kecoklatan. Melekat seakan-akan rambut Kembang Wangi memang berbentuk demikian. Begitu melekat, sama seperti kata-kata terakhir Harum Melati yang akan selalu Kembang Wangi kenang,
“Laki-laki adalah kupu-kupu dan perempuan adalah kembang.”