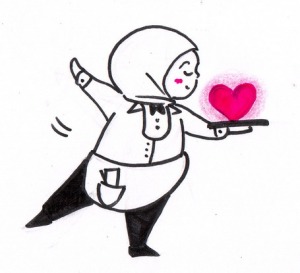Ada satu lagu yang selalu saya dengarkan ketika sedang merasa agak bingung. Lagu itu adalah “Sleeps with Butterflies” yang dibawakan oleh Tori Amos. Sebenarnya saya tidak mengerti makna sebenarnya lagu itu, tapi tetap saja saya mendengarkan lagu itu berkali-kali. Karena saya merasa lagu itu dekat sekali dengan hati. Ada rasa mengenali. Dejavu.
Baru belakangan ini saya dengarkan kembali lagu ini, dan mata saya pun berkaca-kaca. Ternyata maknanya sangat dalam. Mau tidak mau saya terinspirasi dan terciptalah “Kembang Wangi”. Tapi karena maknanya sangat mendalam, saya pun agak kacau dalam menuliskan kesan terhadap lagu ini. Tapi lumayan saja lah. Sekedar hiburan.
Tapi!
Ini adalah cerita yang ku rating “D”. Ada sedikit kevulgaran, tapi bukan itu yang membuat dia “D”. Tapi karena banyak istilah yang akan mengundang tanya, juga terdapat kegelapan yang agak aneh di dalam cerita ini.
Jadi harap hati-hati dalam membaca cerita yang kali ini. Dan seperti biasa biarkan cerita mengalir dan jangan pikirkan teknis dan EYD. Biarkan saja pikiran mengembara. Sesekali saja!
-nyaw, bercerita tentang kembang dan kupu-
***
Kembang Wangi

Jaka merasa heran dengan perubahan drastis kawan dekatnya yang bernama Adi. Beberapa hari yang lalu Adi begitu murung dan mukanya gelap. Kawannya itu sendu dan hampir-hampir sepenuhnya tidak berfungsi. Berhari-hari ia absen kuliah hingga hampir meninggalkan skripsi. Dosen-dosen dan petugas TU kocar-kacir mencari dirinya. Soalnya Adi sudah mendekati batas waktu DO. Sayang sekali kalau ia melewatkan tahun ini hanya karena setitik masalah kecil. Apalagi kalau bukan masalah perempuan.
Adi yang sudah hampir DO itu ditinggalkan kekasihnya. Ia perempuan cantik mungil dan pujaan hati seantero kampus. Jaka tidak heran Adi yang pecundang ditinggalkan kekasih. Mereka memang terlampau jauh. Paras maupun prestasi. Sudah keniscayaan kalau mereka akan berpisah.
Dan Adi tahu itu. Bahwa ia yang payah pasti akan ditinggalkan kekasih. Tapi meskipun Adi sudah dapat meramalkan masa depan naasnya, ia tetap terpukul oleh nasib buruknya. Akhirnya ia pun terpuruk di dalam keadaan nista. Sudah tidak tampan, tidak berprestasi, sekarang juga hampir tampak seperti orang mati. Sungguh memalukan keadaan Adi.
Tapi hari ini Jaka dibuat terheran-heran melihat keadaan Adi. Wajahnya kini cerah, riang, dan senyumnya terkembang. Ia melangkah ringan seakan ada pegas di tumit-tumitnya. Punggungnya tegak bangga dan bahunya lurus sempurna. Saat Jaka menanyakan bagaimana bisa Adi bangkit begitu cepat dari keterpurukannya, ia menjawab,
“Aku bertemu seorang perempuan.”
“Sedemikian cepat?” tanya Jaka.
Adi mengangguk dan Jaka merengut. Klasik. Masalah perempuan diatasi perempuan. Jaka mengomeli Adi habis-habisan. Mengatasi masalah yang diakibatkan perempuan dengan perempuan lain hanya akan mengulang sejarah. Dan kemungkinan penyelesaiannya akan semakin sulit. Karena perempuan pengganti akan sakit hati parah. Kalau sudah seperti itu Adi harus mengatasi dua masalah. Masalah hati laki-lakinya sendiri yang sakit dan masalah hati perempuan itu yang sakit. Merepotkan.
“Dasar bodoh. Terlalu cepat kalau kau mau pacaran lagi!” omel Jaka.
Kali ini Adi menggeleng. Masih saja wajahnya cerah. Senyumnya kini berubah menjadi cengiran. Jaka menjadi heran. Bagaimana bisa kawannya yang hampir DO dan ditinggalkan kekasih begitu riang? Mungkin sebentar lagi kiamat. Mungkin terompet penanda akhir massa sudah akan ditiup. Jaka jadi was-was. Tapi ia tetap penasaran. Adi pun kembali menjawab,
“Bukan pacar, aku hanya bermain bersama seorang pelacur. Pelacur perawan.”
Jaka sudah hendak memarahi kawannya yang bernama Adi. Sudah hendak ia mengingatkannya mengenai penyakit-penyakit menular seksual yang dapat membuat kemaluan panas, gatal, impoten dan sulit pipis. Kalau mengingatkan Adi tentang dosa dan murka Tuhan, Jaka tidak suka. Karena ia bukan kyai atau dai. Ia tidak tahu hal semacam neraka. Ia hanya tahu betapa repotnya sipilis dan gonorrhae dan hal-hal semacam itu. Bodoh sekali Adi melibatkan diri semacam itu.
Jaka sudah benar-benar hendak mengomel dan memarahi. Tapi kemudian ia menyadari sebuah kontradiksi di dalam kalimat Adi. Ia berkata, “Pelacur perawan.” Mana ada hal semacam itu? Kalau sudah ditusuk berkali-kali, mana bisa perawan? Apa mungkin ia spesialis pada laki-laki yang barangnya kecil? Masa iya harus ukur dulu batang sebelum masuk ranjang? Aneh sekali! Jadi Jaka mengulang,
“Pelacur perawan?”
Kali ini Adi mengangguk dengan sikap pasti. Sambil tersenyum dan sesekali nyengir, ia ceritakan mengenai si pelacur perawan. Dan Jaka mendengar semua cerita secara seksama tanpa mengalihkan perhatian. Pada akhir cerita, Jaka putuskan bahwa ia pun akan menemui si pelacur perawan. Hanya karena penasaran.
*
Adi bilang pelacur perawan itu tinggal di sebuah tempat yang serupa lubang. Ironis. Karena ia adalah pelacur yang tidak memainkan lubang. Tempat serupa lubang itu berada di bawah sebuah jembatan layang. Jadi tempatnya berisik sekali. Karena di atasnya mobil lalu lalang dan berbunyi jedak jeduk ketika menyentuh pertemuan ruas jembatan yang sudah mulai renggang. Tapi ketika malam tiba, jembatan layang itu menjadi sepi dan lubang sembunyi si pelacur perawan menjadi tenang. Dan di saat seperti itulah si pelacur perawan akan menyebarkan baunya. Serupa sebuah kembang. Makanya ia bernama Kembang Wangi.
Dan ke lubang di bawah jembatan inilah Jaka pergi. Karena di sana ada Kembang Wangi. Si pelacur perawan yang menyembuhkan kawannya bernama Adi. Dan menurut Adi, konon katanya semua lelaki mendapat hasil yang serupa dengan dirinya. Merasa segar dan hidup. Padahal tidak menusukkan apapun. Hanya bertemu saja dengan si Kembang Wangi. Ketika Jaka menanyakan tepatnya bagaimana itu bisa terjadi, Adi hanya tersenyum dan berkata Jaka perlu menemuinya sendiri.
Oleh karena itu, Jaka pergi, sekitar jam dua dini hari. Ketika orang lain sedang tahajud, Jaka malah pergi mencari pelacur yang bernama Kembang Wangi. Setelah mengendap-ngendap dengan perasaan hati yang tidak karuan dan takut ditodong preman, ketemulah rumah gelap persembunyian si pelacur perawan. Dan benar saja, saking gelapnya rumah itu, tempatnya sudah menyerubai lubang. Tapi masa sih di tempat yang tidak menarik seperti ini tinggal seorang pelacur perawan?
Lama Jaka mematung di depan lubang. Di luar dugaan, terbukalah pintu depan dan keluarlah seorang perempuan. Kulitnya putih mulus dan rambutnya sedikit ikal bergelombang hingga ke pinggang. Matanya tidak terlalu besar tapi bercahaya lembut di bawah bulu mata yang memberi bayang teduh. Hidungnya kecil dan mancung. Bibirnya pun mungil dan merah manis seperti warna jambu air. Pakaian yang dikenakannya adalah sebuah gaun asimetris berwarna hitam. Membalutnya longgar hingga sedikit melayang ketika angin malam bertiup.
Jaka merasakan suatu keanehan. Menurutnya perempuan itu pastilah bukan seorang pelacur. Karena meskipun cukup manis dan menarik, ia tidak menggoda maupun mengundang. Lekuk perempuannya tidak mengajaknya untuk pergi ke ranjang. Mereka hanya menonjol dan membentuk gelombang serupa ombak lautan tenang.
Jadi pada awalnya Jaka merasa telah melakukan kesalahan. Pasti ia salah rumah. Mana mungkin perempuan yang tidak tampak mengundang itu adalah seorang pelacur? Lalu diingatnya cerita Adi. Bahwa Kembang Wangi selalu memakai gaun hitam. Juga meskipun cantik, kau tidak akan pernah mau mengajaknya ke ranjang. Apakah mungkin Jaka tidak salah orang? Maka ia pun bertanya,
“Apakah kamu yang bernama Kembang Wangi? Si pelacur perawan?”
Perempuan manis itu mengangguk dan tersenyum. Bibirnya melekuk tapi Jaka tidak merasa itu mengundang. Bagaimana bisa? Padahal harusnya semua batang bereaksi bila bertemu perempuan cantik tanpa pertahanan di tengah malam. Tapi tidak. Jaka tidak merasakan desiran atau aliran darah apapun. Ia hanya merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang manusia. Dan ia sama sekali tidak ingat bahwa yang di hadapannya adalah seorang pelacur perawan.
“Ya betul. Silakan masuk Kang.”
Dengan sebuah gamitan kecil, Kembang Wangi menarik Jaka ke dalam lubang. Pintu lubang itu tertutup dan Jaka pun memasuki sebuah dunia yang di luar duganya. Tidak pernah ia kira di bawah jembatan berisik dan hitam, terdapat sebuah rumah berisikan seorang perempuan semacam Kembang Wangi. Jaka merasa menemukan sekuntum mawar di tengah got. Rasanya aneh sekali.
Dalamnya rumah seorang pelacur perawan ternyata pun di luar dugaan. Biasa sekali. Jaka pikir mungkin akan hiasan-hiasan seronok semacam isi toko sex toys Belanda. Atau malah kebalikannya, agak seperti kuil tempat suci sehingga lelaki kehilangan selera. Tapi tidak. Isi rumah itu biasa saja. Ada dua buah kursi, sebuah meja kayu dan lemari buku yang agak melompong. Terdapat sebuah ranjang sederhana tenpa renda. Di sebuah sudut tersembunyi dapur dan di dekatnya ada kamar mandi. Ya sudah itu saja isinya. Tidak menghilangkan maupun menggugah selera.
Meskipun begitu, Jaka tetap menelan ludah. Bagaimana pun itu adalah rumah seorang pelacur dan ia adalah seorang pelanggan. Jaka tidak yakin dengan tindakan apa yang harus diambilnya. Haruskah ia bersikap cool dan menyilang kaki. Haruskan ia mengeluarkan rayu? Jaka tidak yakin. Jadi ia mengikuti kebiasaan yang ia lihat di film. Ia pun bertanya,
“Berapa tarif sejam?”
“Sebungkus nasi kuning dan sebuah cerita untuk sebuah malam.”
“Hah? Goceng?”
“Goceng.”
Bibir Jaka mulai menipis rapat. Ia bingung dengan perkembangan situasi ini. Sebenarnya tempat pelacuran macam apa ini? Pelacur mereka tidak menggoda dan didiskon. Harusnya kan di sini lelaki menghabiskan asa di dalam batang, kok jadi begini? Ah sudahlah. Mungkin ini permainan agar Kembang Wangi membuat otaknya berputar bingung. Kalau sudah begitu mungkin laki-laki yang keblinger akan lupa untuk meniduri. Jadi untuk seterusnya pelacur itu perawan dan dapat keuntungan. Licik sekali!
Jadi Jaka yang masih muda dan berotak lihai cerdik, memutuskan mengikuti permainan. Ia merasa bahwa pelacur itu akan mempermainkannya. Mana mungkin lelaki nafsu tidak akan menerjang. Apalagi Kembang Wangi sudah mencap dirinya pelacur dan dapat dikangkang. Tidak mungkin ada pelacur yang perawan. Kalau mengaku perawan sih banyak.
“Okay.”
Tanpa banyak kata Jaka bangkit dari kursi dan menarik tubuh Kembang Wangi. Tubuh itu sempat tersentak kaget tapi kemudian melemas dalam pasrah. Jaka mendekatkan mukanya ke muka Kembang Wangi. Tatapannya mengunci hendak mengambil sebuah cium kasar. Tapi mata Jaka yang seharusnya mengirimkan pesan kekerasan dan kekuasaan malah melihat sesuatu yang lain di dalam mata Kembang Wangi yang jernih. Hal yang dilihat di dalam kedua mata si pelacur perawan membuatnya terenyuh dan lemas.
Di dalam mata coklat Kembang Wangi, Jaka melihat suatu kejernihan yang mengingatkannya pada saat-saat ia masih seorang bocah. Saat itu ia masih bau kencur.
Ah itu perumpamaan yang klise. Tapi lebih tepatnya saat Jaka masih bau seperti anak ayam yang kebasahan. Saat ia masih nakal dan terkadang keluar umbel hijau dari hidungnya. Badannya masih mungil dan hanya sepinggang lelaki dewasa. Kegemarannya adalah mencuri buah mangga tetangga. Meskipun masih sepet asam dan hijau. Ia akan bersusah payah memanjat hingga ke pucuk paling atas. Itulah kegemaran Jaka yang masih berumbel hijau.
Pada suatu hari terlihat sebuah mangga, jauh di pucuk pohon tetangga. Mangga-mangga yang lain masih hijau, tapi yang satu ini berbeda. Yang ini sudah ranum sendiri. Tidak hanya umbel Jaka yang melorot turun naik, air liurnya pun turut mengalir seperti sungai deras.
Tentu saja Jaka tidak dapat melewatkan mangga itu. Kapan lagi datang keranuman semacam itu lagi? Ah Jaka mungil perlu mengambil si ranum itu! Jadi dipanjatlah pohon tetangga, dengan bersembunyi-sembunyi dan berusaha tidak berbunyi. Karena hari itu Jaka menjadi bandit. Jadi penjahat. Jadi maling. Beringsut-ingsut ia menarik tubuh hingga ke pucuk. Tangannya terentang dan tergapai hingga ia melihat sesuatu yang mengejutkannya dari atas pucuk itu.
Jaka mungil melihat putri remaja tetangganya itu bersalin baju. Tubuhnya mulus dan ia memakai suatu baju yang berbeda dengan baju-baju milik Jaka mungil. Bentuknya membelit dada bagian atas si putri remaja. Dan ketika ia membuka kait belakangnya, terlihat bentuk-bentuk yang Jaka tidak punya. Jaka tidak tahu apa nama bentuk-bentuk itu. Tapi ia merasa malu. Merasa tidak layak melihatnya. Jadi ia berpaling. Terlalu cepat.
Dan Jaka terjatuh.
Jatuh dari pohon tetangga.
Ke dalam kubangan coklat.
Coklat seperti mata Kembang Wangi.
Jaka melepaskan tubuh Kembang Wangi dengan sebuah sentakan tiba-tiba, membuat si pelacur perawan hampir terjatuh. Keringatnya mengalir deras. Kenapa tiba-tiba ia teringat pada dosanya yang telah sekian lama? Kenapa semuanya terlihat di dalam jernih mata Kembang Wangi?
Dengan tergesa-gesa Jaka menjauh. Ia merogoh-rogoh isi saku dan mengeluarkan selembar uang. Goceng. Sesuai perjanjiannya dengan Kembang Wangi. Diulurkannya uang itu dengan tangan yang gemetar. Si pelacur perawan mengambil lembaran itu sambil berkata,
“Lalu ceritanya?”
Jaka menggeleng keras-keras. Ia lalu menawarkan selembar uang lainnya. Lembaran berwarna biru. Bertuliskan “rupiah lima puluh ribu”. Tapi Kembang Wangi menutupkan tangan Jaka dan menggelengkan kepala. Ikalnya bergoyang ketika ia berkata,
“Tidak. Aku tidak butuh lima pulu ribu. Aku butuh ceritamu. Berarti kau berhutang padaku.”
Jaka meneguk ludah. Pikirannya nanar dan berputar. Dia hendak membantah dan memaksakan uang biru itu ke dalam tangan si pelacur, tapi ia keburu takut melihat jernih mata coklatnya. Jadi ia mundur, mengangguk, dan berjalan cepat keluar dari rumah serupa lubang itu. Jalan? Mungkin tepatnya Jaka berlari seperti anak kelinci dengan buntut terbakar. Ya secepat itulah Jaka berlari.
Dan sepanjang lari itu Jaka bertanya-tanya, apakah gerangan yang berada di dalam mata Kembang Wangi? Mungkinkah semacam kutukan gypsy, ataukah santet dukun? Yang pasti Jaka merasa resah dan gelisah. Ia pun menyesali keputusannya untuk mendatangi Kembang Wangi, si pelacur perawan.
*
Sudah selang beberapa hari dari saat Jaka mendatangi rumah lubang milik Kembang Wangi. Jaka ingin melupakan kunjungan singkatnya itu. Ia pun ingin merelakan goceng yang seharusnya dia pergunakan semalam suntuk. Juga ia berniat untuk tidak pernah membayarkan hutangnya yang berbentuk satu cerita itu. Tapi entah mengapa Jaka tidak dapat melakukan semua itu.
Selama berhari-hari itu, Jaka teringat pada Kembang Wangi. Pada ikal rambutnya. Pada kulit bersihnya. Pada lekuk lembutnya. Tapi terutama ia tidak bisa lupa pada mata coklat jernihnya. Mata yang membuatnya terkenang pada dosanya. Hingga ia merinding dan bulu-bulu tangannya berdiri ngeri.
Tapi ada suatu kepuasan di dalam menatap dosanya. Kepuasan dalam kejujuran yang sedikit sakit dan nyeri. Mengingatkan Jaka pada saat ia melepaskan kepolosannya untuk pertama kali. Ketika ia tidak sadar apa itu sebenarnya makhluk perempuan. Seperti apa sih yang berada di balik baju itu.
Jaka malu sekaligus puas tertantang. Tapi ia masih enggan mengulang pengalaman itu. Karena meskipun itu memuaskan, tetap saja itu adalah dosa yang terkenang. Sungguh menyakitkan melihat kesalahannya sendiri.
Tapi entah mengapa Jaka merasa perlu menantang jernih mata itu sekali lagi. Karena entah apa yang berada dalam jernih itu kali ini dan nanti. Apa lagi kejujuran yang akan Jaka lihat? Jaka penasaran. Dan sekali lagi, sekali lagi Jaka kembali kepada rumah lubang Kembang Wangi.
*
Dan sekali menjadi dua kali. Lalu dua kali menjadi tiga kali. Tiga kali menjadi berkali-kali hingga tidak terhitung lagi. Dan selalu saja pada akhir pertemuan, Jaka hanya mengacungkan selembar goceng. Dengan tangan yang gemetaran dan keringat bercucuran. Dan selalu saja Jaka berhutang pada si pelacur perawan. Hal yang sama hingga Kembang Wangi sendiri pun jengah mengingatkan. Hingga pada suatu hari ia berkata,
“Hutang ceritamu sangat banyak Jaka! Ya ampun…. Ya sudah! Kamu jangan pulang malam ini! Sini kamu duduk di sini sambil ngopi-ngopi. Biar aku saja yang bercerita!”
Jadi dengan terpaksa Jaka duduk di salah satu kursi di rumah serupa lubang itu. Ia memilih kursi yang dekat pintu. Di bawah sadar ia sudah bersiap minggat. Kembang Wangi melihat gelagatnya dan hanya menghela napas. Dengan santai ia duduk dan menatap heran tamunya malam itu. Kembang Wangi pun berkata,
“Belum pernah aku punya pelanggan sesulit kamu sebelumnya.”
Jaka merasa tertarik dan bertanya, “Memangnya yang lain seperti apa?”
“Yang lain selalu langsung bercerita begitu menatap mataku. Dan mereka sangat puas setelah menceritakan segalanya padaku.”
“Oh begitu?”
Jaka bergerak tidak nyaman dan Kembang Wangi kembali mendesah dengan keras. Lagi-lagi ia menyatakan Jaka sebagai pelanggan yang susah lalu ia mulai bercerita. Cerita yang aneh dan sedikit magis. Mengenai keluarganya yang semuanya pelacur. Tapi semuanya perawan. Karena mereka memiliki kemampuan yang sama. Kemampuan dalam membuat lelaki lepas.
“Lelaki yang lepas itu bukan lewat sini.” Kembang Wangi menunjuk antara kaki. “Tapi lelaki yang lepas itu ada di sini.” Kembang Wangi lalu menunjuk hati.
Jaka mendengarkan cerita aneh ini dengan tertarik. Ia tidak lagi memikirkan hal-hal aneh yang terlihat di dalam mata Kembang Wangi. Ia hanya menyimak kata-kata yang keluar dari bibir yang begitu ekspresif. Mungil tetapi sesekali sedikit menyungging atau monyong saking senangnya bercerita. Lalu tubuh Kembang Wangi bergoyang dengan sedikit terlalu bertenaga ketika dengan gemas ia melanjut ceritanya.
Kembang Wangi menceritakan mengenai bagaimana ibu dan nenek-neneknya kehilangan keperawanan. Katanya itu karena akhirnya lelaki-lelaki yang biasanya hanya ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kalau sudah menjadi kupu-kupu, lelaki itu akan terbang pergi meninggalkan para pelacur tetap perawan. Tapi tidak dengan kupu-kupu yang satu itu, yang menjadi bapak dan kakek-kakeknya.
“Akan datang satu laki-laki kupu-kupu. Dia akan terbang kembali dan mengambil perawan kami.”
Begitu kata Kembang Wangi dengan begitu pasti. Jaka pun tergelitik dengan pernyataan ini. Mau tak mau ia yang tadinya grogi, angkat bicara juga. Karena ia adalah lelaki yang tidak bisa tidak penasaran. Ia bertanya,
“Lalu setelah perawan itu diambil, apa ia akan membawa ibu dan nenek-nenekmu pergi?”
Di sini bibir mungil Kembang Wangi merapat. Pipinya memerah dan alisnya berkerut ke atas. Ujung bibirnya berkedut dan sebuah titik air mata terjatuh ketika ia menjawab,
“Tidak. Semua laki-laki kupu-kupu pasti pergi.”
Jaka terdiam. Dilihatnya gemetar di dalam tubuh Kembang Wangi. Mukanya berpaling tersembunyi di balik ikal-ikal. Tangannya terkepal gelisah di atas pangkuan. Dan Jaka tidak dapat menahan diri. Ia berdiri dan mendekat untuk memberikan sebuah rangkul.
Tubuh Kembang Wangi melunglai di dalam peluknya. Lalu Jaka menghadapkan muka si pelacur perawan menghadap dirinya. Mata mereka kembali beradu. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini yang terlihat di dalam jernih itu berbeda. Berbeda sama sekali. Malam ini, di dalam jernih mata Kembang Wangi, Jaka melihat kisah yang lain. Kisah hidup Kembang Wangi yang sepi. Karena selalu ditinggalkan lelaki yang bersikap seakan-akan mereka kupu-kupu.
Dan Jaka kembali tidak menahan diri. Ia menanamkan sebuah cium. Lalu satu cium menjadi dua. Dua cium menjadi tiga. Lalu tiga cium menjadi banyak ciuman. Banyak hingga hampir tidak terhingga. Dan mereka berguling ke atas ranjang si pelacur perawan yang tidak berenda. Bergulingan hingga pelacur itu sudah tidak lagi perawan dan jaka yang tadinya hanya ulat menjadi kupu-kupu.
Dan seperti sudah diketahui Kembang Wangi, semua kupu-kupu itu pergi. Meninggalkannya hingga jiwanya sepi. Tapi kali ini sepi itu terasa hampir seperti mati. Karena Kembang Wangi punya rasa pada si pelanggan paling susahnya yang bernama Jaka.
Selain itu Jaka punya hutang yang sangat banyak pada Kembang Wangi. Hutang cerita yang sangat banyak! Kembang Wangi yang sial. Sudah dihutangi begitu banyak, ia pun penasaran dengan cerita-cerita dari kekasih hatinya bernama Jaka.
Ya. Kita doakan saja Jaka akan terbang kembali. Siapa tahu ia kupu-kupu jenis beda lagi!