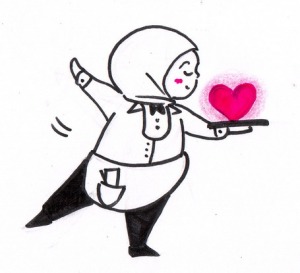Hari ini karib saya menikah. Sebenarnya saya ingin menuliskan suatu cerita cinta pastel, tapi saya sedikit tidak mood untuk itu. Karena satu dua hal yang bersifat pribadi dan agaknya tidak bisa saya jabarkan dengan jelas. Oleh karenanya saya buat cerita lain saja. Meskipun tidak jelas fiksi atau apa. Tidak ada plot dan lebih seperti monolog. Tapi saya senang membuatnya. Karena malam sebelumnya saya membaca kumpulan cerpen berjudul “Numi” yang ditulis Yetti Aka. Jarang-jarang saya terpengaruh tulisan orang, tapi rasanya saya terpengaruh. Mungkin karena saya niatkan untuk terpengaruh. Atau mungkin karena gaya setengah bermimpinya itu saya sangat kenal. Jadai saya menulis cerita ini. Juga karena saya suka hal-hal yang berkaitan dengan semesta, ruang hampa dan dualisme sifat cahaya. Jadi ada sedikit rasa science fiction. Tapi dalam bahasa perempuan yang susah dimengerti dan benar-benar surrealis. Tidak masalah sih. Sekadar rekreasi.
Selamat membaca dan jangan memerhatikan hal-hal teknis. Karena rugi memikirkan hal-hal serius dan aturan-aturan yang sebenarnya berubah-ubah seenak jidat.
-nyaw, dual-
***
Luas Menghampar Hingga Tidak Berbayang
Ketika saya tahu perkataan buruk yang dikatakan perempuan itu, saya marah. Saya marah dan memanas. Biasanya saya tenang dan semilir seperti sepoi yang malas. Tapi setelah mendengar kata-kata buruk itu terlontar, saya marah. Maka saya yang biasa santai dan tak banyak komentar, berubah menjadi ribut dan penuh teriak.
Saya bisa merasakan bahwa bobot tubuh saya yang sangat banyak berpisah dan menjadi petak-petak yang berlari ke segala arah. Petak-petak itu kuat dan mereka melolong menuntut balas. Mereka berderap dengan rambut berurai panjang dan alis mengernyit. Mata mereka adalah kilau permata biru dan ungu dengan sedikit emas. Mereka berlari berderap maju menuntut balas dan mengguncangkan segala yang berada di depan mereka. Lalu mereka berkata,
“Diam perempuan kecil! Diam! Kamu pikir kamu tahu artinya jadi wanita tapi kamu berpura-pura! Kamulah penipunya! Kamulah yang culas! Kamu menjebak lelaki itu untuk menikahi seorang elegan padahal kamu masih kecil dan kamu masih tidak tahu apa-apa.”
Dan mereka yang berderap kecil, yang melolong menuntut balas tidak hanya dua atau tiga. Mereka ada tujuh, sepuluh dan kadang tiga belas. Mereka serupa peri-peri kecil yang lepas ketika hati saya tidak terima dengan keadaan dan ingin memberikan balas. Mereka berlarian dengan beringas ketika jiwa saya tidak tenang dan terpenjara dalam raga yang saya tahan agar tidak bersikap keras. Mereka adalah peri-peri kecil yang tidak dapat saya tahan berpisah dari tubuh saya yang bobotnya sangat banyak. Dan mereka tidak hanya dua, tiga atau lima. Mungkin tujuh, sepuluh dan bahkan berbelas-belas.
Lalu mereka berlari dengan ribut. Seperti angin yang gemuruh dan tak kenal kasih. Mereka berteriak dan melolongkan hal-hal yang mereka benci. Mereka terbang ke langit luas dan membuat ribut. Lalu awan-awan akan terganggu lalu menggelap dan langit menjadi kelabu. Dan mereka, peri-peri kecil, pecahan dan retakan dari jiwa yang tidak tenang ini, menggemuruh dan terus berlari. Berderap dan mencari arti. Tapi dengan ribut, dengan tidak jernih.
Langkah-langkah mereka kecil, tapi tiap langkah adalah sebuah tapak angin ribut. Hentakannya dapat merubuhkan segala yang berada di situ. Dan hentakan itu tidak akan berhenti hingga mereka memperoleh jawab. Mengapa perempuan itu berpikir dia berhak mengaku wanita dan mengapa lelaki itu membiarkan dirinya menjadi seperti itu.
Tidak banyak yang memberi jawab, lebih banyak yang ingin ikut. Ikut ribut. Ikut riuh. Ikut mencari balas pada perbuatan yang tidak teduh. Dan yang ingin ikut itu akan berkata,
“Biar saya buat perempuan itu menggigil kedinginan hingga demam.”
“Biar saya buat perempuan itu gamang hingga hatinya tak lagi lengang.”
“Biar saya buat perempuan itu bingung hingga ia tidak lagi tahu apa yang ada di hatinya yang paling dalam.”
Sebenarnya saya sangat marah hingga ingin bilang,
“Pergi, pergi kalian. Bersama pecahan-pecahan diri saya yang tidak sedikit. Pergilah kalian dalam bilangan lima, tujuh, atau mungkin berbelas-belas.”
Mata saya berkilat-kilat. Menimbang kemarahan dan keinginan saya untuk mengirimkan pecahan-pecahan jiwa saya bersama mereka yang mengerti caranya menuntut balas. Tapi kemudian saya akan mengaca, dan terlihat kilat emas yang berburu biru dan ungu seperti lebam. Lebam seperti hati saya yang terluka dan ingin menuntut balas. Geram dan getir karena tidak terima pada perkataan tidak baik pada seorang teman.
“Tapi itu namanya cinta. Temanmu cinta dia dan tentu kamu perlu terima.”
“Saya terima dari sejak semula. Saya malah sangat bahagia. Tapi saya marah ketika tahu perkataan perempuan itu padahal temanku tidak sedikit pun seperti itu.”
“Tapi dia cinta, dia sabar, dan dia memaafkan.”
“Dari jaman sebelum waktu ini. Ketika saya dan dia tidak berupa seperti ini, dia selalu begitu. Dia cinta lalu dia menghamba. Bahkan dia membunuhku berkali-kali demi perempuan-perempuannya!”
“Maka sebenarnya kamu bukan tidak terima perempuan itu, tapi kamu takut. Takut bahwa kamu akan dikhianati sekali lagi seperti dulu dulu dan dulu. Lalu kamu akan mati lagi lagi dan lagi. Padahal kamu selalu hidup kembali. Berkali-kali. Dan kamu, setiap waktu jiwamu dijaga. Seakan-akan ia tidak pernah ternoda. Lalu untuk kali ini, yang tampak seperti kali itu, lalu mengapa kamu takut dan mengapa kamu hanya memikirkan jiwamu secara kerdil. Padahal jiwamu luas. Luas membentang hingga ke ujung semesta. Hingga cahaya tidak lagi membuat bayang. Dan kamu dan dia dan perempuan-perempuan itu adalah satu. Pecahan-pecahan semesta yang bercerita dan suatu saat akan kembali. Dan pada saat ia melakukan apapun untuk perempuan-perempuannya, ia melakukan segala-galanya untuk dirinya dan dirimu dan seakan-akan dirimu adalah dirinya yang berbuat semuanya untuk diri kalian sendiri. Lalu mengapa kamu ribut, seakan-akan jiwamu kerdil.”
“Tapi ini berulang. Dan dia akan menghilang dan mati. Lalu hanya tersisa anak-anaknya dan mereka akan seperti itu lagi. Dan saya akan menjadi saksi lalu juga mati dan merasa sedih akan peristiwa-peristiwa yang berulang dan selalu terjadi.”
“Biarlah. Biarlah seperti itu. Untukmu sendiri, kau hanya pikirkan apa jiwamu bisa luas. Keperluanmu hanya sampai di situ.”
Sebuah titik air mata kemudian menetes. Geram dan getir tetap mengaduk hati. Tapi perlahan-lahan aku memanggil mereka, para peri, yang mendesak keluar dan memecah. Kupanggil mereka dan kuceritakan mengenai hal-hal yang indah. Hal-hal yang membuat senang. Dan kuceritakan mereka mengenai luasnya hati dan jiwa kebutuhannya untuk menjadi tenang. Dan kukatakan pada mereka kalau mereka tidak dapat menjadi semilir yang menenangkan setidaknya mereka perlu diam. Kalau mereka tidak dapat menyampaikan pikiran yang baik, maka mereka sebaiknya tidak perlu membentuk tangan menjadi kepalan.
Tentu saja mereka pada awal resah dan meremang. Tapi mereka tahu bahwa tugas mereka adalah mencari arti dan mendongeng mengenai hal-hal yang sebenarnya bisa terjadi. Hal-hal indah dan hal-hal yang baik. Hal-hal yang menenangkan dan menyenangkan seperti doa. Daripada menjadi angin yang ribut, lebih baik menjadi sepoi semilir yang menyejukkan. Meskipun bisa, tidak berarti harus dan tidak berarti itu tepat.
Maka satu per satu, tiga, lima dan berbelas-belas kembali mengisi retak di dalam jiwa dan hati. Berdiam diri dan sudut dan relung. Tidak suka pada ketidakadilan apalagi bila itu dekat sekali. Tapi semuanya saling bergumul dan terkadang berdiskusi. Bahwa mungkin ini memang harus terjadi. Mungkin memang maunya Tuhan begini. Lalu mengapa perlu kesal hanya karena kata-kata yang belum tentu memiliki arti. Mungkin itu tidak sengaja. Mungkin itu bukan kata-kata untuk menyakiti hati. Cinta mungkin berarti memaafkan berkali-kali.
Mereka, peri-peri kecil itu berbisik dan bertepuk tangan kecil. Katanya,
“Iya iya iya! Cinta adalah memaafkan berkali-kali!”
“Dan lalu jiwa akan luas dan membentang hingga tidak memiliki bayang?”
“Iya iya iya! Kadang cinta sehebat itu!”
Dan satu per satu mereka bersepakat untuk berdiam. Beberapa mencoba-coba untuk berpisah. Bukan untuk ribut dan melolong membuat semuanya terganggu. Tapi mereka berpisah, dengan sebuah langkah lompat kecil yang lucu. Dan mereka ikut kemana anak-anak angin berhembus. Lalu singgah di dalam mimpi-mimpi orang-orang terkasih sambil berkata,
“Yuk main yuk. Karena akhir-akhir ini kamu susah ditemui.”
Dan mereka mengajak main hingga orang-orang yang saya kasihi merasa bingung. Besoknya mereka bilang, “Saya bermimpi tentang kamu.” Dan saya akan menjawab sedikit lidah kelu, “Ha iya, biarkan saja seperti itu. Mungkin saya memikirkan kamu.” Lalu mereka akan menjawab, “Berarti kamu rindu.” Saya tentu tertawa dan berkata,
“Ya saya rindu dan saya cinta semua kamu. Karena kamu dan aku berasal dari hal yang sama. Dan bila kamu berbahagia, maka sebenarnya sebuah bagian jiwa saya ikut bergembira. Dan bila kamu merasa terserak, sebenarnya tanpa sadar sedikit jiwa saya akan merasa rendah. Jadi sebenarnya memang benar saya pasti cinta dan saya rindu hingga saya datang dalam mimpi-mimpimu. Karena saya dan kamu memiliki jiwa yang luas dan membentang hingga cahaya tidak lagi membayang. Dan pada batas yang seperti itu, kita jadi tahu bahwa banyak sekali kemungkinan untuk berbahagia. Dan keinginan untuk merasa utuh adalah angan-angan. Karena sebenarnya seharusnya semua orang merasa sedikit retak agar dapat saling butuh. Juga setelah tidak sampai keutuhan itu maka kita akan mencari Dia yang tidak membutuhkan apa-apa.”
Jadi tentu. Tentu saya rindu dan cinta kalian. Sampai jiwa saya terserak bercerita macam-macam. Baru-baru ini saya ingin bercerita tentang kemarahan saya pada perempuan yang menghina teman saya. Sampai-sampai saya sangat geram. Tapi lalu kemarahan itu teredam. Karena saya sadari bahwa apapun yang dibutuhkan suatu bagian kecil akan baik bagi jiwa saya sendiri bertumbuh. Maka saya memutuskan untuk mengambil pesan dari kejadian ini. Bahwa cinta adalah memaafkan berkali. Lagi lagi dan lagi. Dan hidup adalah berani untuk menjalani peran. Berkali-kali hingga nanti. Dan hidup adalah memberi tanpa perlu merasa teriris. Selalu selalu dan selalu.
Hanya melakukan melakukan dan melakukan.
Selebihnya adalah kembali pada Tuhan.