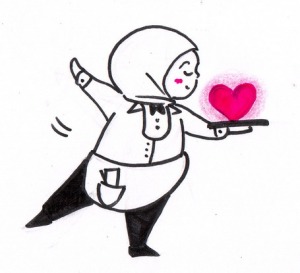Aduh saya makin jarang menulis. Menulis fiksi maksudnya. Sebenarnya saya kembali kerja di bidang yang dulu, kosmetika. Tapi bidangnya sedikit beda. Agak seperti semi marketing, branding dan sedikit menyentuh konsep produk. Belum sepenuhnya jelas, karena saya baru seminggu. Meskipun baru seminggu, saya sudah mengerjakan sesuatu yang mini-mini imut. Saya menuliskan beberapa tulisan nonfiksi. Mungkin ini memendekkan napas fiksi saya, karena tulisan nonfiksi memiliki struktur yang lugas dan biasanya saya menulis dengan mengalun.
Tapi tidak masalah buatku, fiksi maupun nonfiksi. Dua-duanya saya suka. Karena dua-duanya sebenarnya cerita dari hati. Ya! Bahkan artikel mini sekalipun! Dan kata-kata hyper dalam tulisan nonfiksi tidak hanya untuk memboost omzet. Itu tidak benar. Sebenarnya kata-kata “keren” itu hanya untuk mengetuk pintu rasa calon pembeli, bahwa,
“Iya loh, produk ini memang benar-benar dirancang dengan serius dan kamu yang beli pasti merasa bahagia dan nyaman.”
Bukankah semua karya, bukan hanya kosmetika, tapi makanan, minuman kemas, pakaian, dll, semuanya berprinsip demikian? Bahwa ini adalah sebuah sajian dari hati, coba kamu rasakan?
Sebenarnya begitu pekerjaan saya sekarang. Tidak lagi menjadi peramu, tapi menyampaikan perasaan para peramu di dalam kata-kata yang tidak terucap dalam produk yang nggak bisa nyanyi. Pekerjaan yang seru ya. Mungkin di masa depan krim-krim itu bisa ngomong. nah kalau sudah begini saya mungkin nganggur lagi. Tapi itu gak masalah, karena manusia perlu hidup dengan ridha.
Meskipun saya banyak nulis nonfiksi, saya sempatkan menulis fiksi hari ini. Empat halaman saja. Napas saya berkurang drastis. Tapi secara pribadi, saya merasa lebih memikirkan kata-kata yang tepat dalam menggambarkan apa yang saya rasakan dan pikirkan. Jadi empat halaman ini lumayan. Meskipun gak hebat, tapi saya menikmati ketelitian saat menulisnya.
Selamat menikmati dan seperti biasa, jangan pikirkan hal-hal teknis dan semacamnya dan semacamnya. Enjoy!
-nyaw, kembali ke abu-
***
Bisikan di Dalam Semilir
Bisikan di dalam semilir terdengar lirih. Halus tuturnya mengajak Nira pergi. Katanya,
“Ayo pergi, ayo kita pergi.”
Nira diam dan tertegun. Dia sudah enak duduk bergeming di guanya yang hening. Tidak ada riuh, tidak ada ribut. Hanya ada Nira dan gema santun irama batu. Dan sesekali terdengar gemiricik aliran air di sela-sela pori batu. Tapi selebihnya hanya ada Nira dan lowongnya gua batu. Dan damai. Damai sunyi dalam tenangnya jiwa yang menyendiri.
“Tapi jiwamu terbuat dari angin, kamu sebenarnya tidak seperti ini.”
Nira merengut. Dia tahu bahwa semilir tidak berbohong hari ini. Tapi dia terlanjur senang pada lowong guanya yang hening. Di sana hanya ada Nira. Dan hati Nira. Dan pemikiran Nira. Dan mungkin Tuhan. Dan mungkin malaikat-malaikat. Dan mungkin beberapa demit. Tapi selebihnya hanya ada jiwa raga Nira dan beberapa kawan. Tak kurang, tak lebih.
“Tapi jiwamu dari angin, kamu perlu berhembus dan bernapas.”
Maka Nira menuruti bujuk di dalam semilir. Karena jiwanya tidak diperuntukkan untuk menjadi lembam seperti batu. Juga bukan untuk menjadi lentur seperti ombak laut. Ia juga tidak membara hangat seperti unggun. Ia adalah angin yang harus berhembus. Mengantarkan napas ke dalam paru-paru. Napas yang hidup dari nyala jiwa di dalam dada.
Jadi Nira beranjak dan berdiri. Menuruti paksa esensi dalam hati. Meskipun terasa berat meninggalkan sejuk gema gua batu. Dan berat meninggalkan suara gemiricik air di dalam sela-sela liat itu. Tapi Nira perlu pergi. Seperti angin yang selalu bergerak. Mengurai diri menjadi napas dalam diri sesama manusia seperti Nira.
Lalu Nira berjalan, sedikit tertatih-tatih. Ia pegal terlalu lama mengurung diri. Perlahan-lahan ia berjalan mengikuti ke mana semilir pergi. Nira tidak pernah bertanya pada semilir ke mana akan dibawanya kaki-kaki ini. Seperti pengalaman-pengalaman yang dahulu, ia belajar pentingnya untuk tidak bertanya. Tapi dari pengalaman yang dahulu, Nira tahu pentingnya untuk menjadi jeli. Ketika seni menjawab “Iya” dan “Tidak” adalah sesuatu yang mesti. Dan terkadang diperlukan sebuah jawaban “Mungkin”.
Jadi Nira tertatih tapi ia tetap berjalan dengan kecepatan yang membuatnya tidak banyak berhenti tapi cukup membuatnya nikmat melihat keluar jendela tatap. Dilihatnya di luar sana orang-orang yang berlari kencang atau teronggok sama sekali. Dilihatnya di luar sana orang-orang yang begitu sibuk untuk berlari ke satu arah hingga ditabraknya orang di depannya dengan kencang.
Nira menggelengkan kepala. Tiga tahun ia berada di dalam gua, dan orang-orang masih saja seperti itu. Seperti tidak ada besok dan hanya kemarin. Seperti sedang menahan pipis empat liter di dalam ginjal berkapasita tiga koma sembilan. Lalu pipis itu tidak tertahan, maka orang itu berlari dengan bergegas hanya untuk sekedar membuang kotoran.
“Aduh semilir, kamu kok mengajakku ke dunia seperti ini lagi?”
Semilir terkekeh dan bersalto riang. Tidak diindahkannya Nira yang merasa heran. Malahan ia merasakan sebuah rasa jenaka. Dengan nada senandung yang halus penuh sayang, dikatakannya,
“Aduh Nira, kamu kok nanya? Dunia ya masih begini saja. Dunia ini lama. Tapi kamu yang hari ini selalu baru. Sudah, mendingan kamu terus jalan. Karena angin itu perlu berhembus dan tidak boleh diam.”
Nira mengangguk mengerti dan terus berjalan. Dengan tertatih dan lamban. Seperti semilir angin di sela dedaunan. Hanya sebuah gerak ringkih atau gemetar yang menunjukkan ia ada dan tidak pernah diam. Seperti itulah Nira kini berjalan.
Dan berjalan seperti itu adalah tidak masalah. Yang penting senantiasa bergerak dan menghembuskan napas. Juga memasang jeli mata agar tidak melewati hal-hal yang dapat memperdalam dan memperkaya jiwanya. Karena suatu hari itu jiwa itu kembali kepada yang empunya. Dan semua yang ia dapatkan di dunia ini akan diceritakannya kembali.
Maka cerita-cerita yang akan disampaikan kembali ke langit itu perlu disampaikan dengan halus. Dengan bahasa yang indah dan bersih. Bersih jujur menurut tutur hati. Bercerita semuanya padahal semuanya itu sudah diketahui. Tapi cerita dari para pendongeng selalu baru. Selalu baru.
Setiap dongeng selalu baru, meskipun hanya itu-itu saja. Setiap sejarah itu tidak pernah tua, meskipun hanya mengulang-ngulang saja. Dan setiap jalanan tidak pernah sama, meskipun yang itu-itu saja. Nira tahu itu. Dia tahu. Jadi dia ikuti saja hembus semilir membawa kaki-kakinya ini. Entah ke mana, tapi sepertinya ke sana. Tempat yang ia kenal sudah lama.
Semilir membawa Nira kembali ke kota yang sudah seperti sebuah tungku. Apinya besar dan membakar. Air bergolak dan mengantarkan didih uap ke dalam udara. Dan langit yang seharusnya berwarna biru, berwarna serupa abu. Kelabu dari jelaga tungku. Kelabu dari manusia-manusia pencari emas yang dijadikan arang kayu karena lupa pada asalnya dulu.
“Kembali ke dunia abu?”
“Iya, kembali abu.”
“Sanggupkah saya?”
“Selalu.”
Maka Nira kembali melangkah. Kaki-kakinya beranjak maju, menginjak kembali tanah dunia yang berwarna abu . Kakinya menjejak dan terbanglah abu itu menjadi kepulan-kepulan debu. Debu itu menghambur dan melebur lalu berputar membentuk bola. Dijadikan ajang bermain sepak oleh semilir yang tidak tahu menahu dari mana kelabu itu berasal.
Tapi Nira tersenyum. Biarkan semilir bermain dan tak perlu tahu menahu mengenai kisah asal mula kelabu. Nira sendiri yang tahu pun juga tak perlu ragu. Karena abu pun sebenarnya dapat menjadi kehidupan. Bukankah semua tanah berasal mula dari debu abu yang memunculkan urat-urat hijau serupa sulur?
Jadi Nira melangkah maju. Tertatih-tatih tapi tetap maju. Dia kembali ke dunia abu. Dulu ia akan bertanya apa yang bisa ditawarkan dunia ini kepadanya. Tapi itu dulu. Sekarang ia tahu bahwa tak bisa lagi ia mengharapkan sebuah pemberian dari dunia abu, ia hanya bisa mengharap dari jejak-jejaknya muncul sulur dan bayarannya dari yang Punya. Hanya dari yang Punya.
Tidak ada pemberian yang lebih baik dari itu.
Jadi jiwa Nira bergerak dan menari. Tidak selincah dulu. Tapi tetap bergerak seperti riak yang mengalun. Perlahan, perlahan saja. Asal tetap laju.